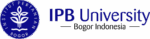Komnas HAM dan PSP3 IPB University Tegaskan Pangan Adalah Hak Asasi Manusia

Di tengah gencarnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek Food Estate, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University menggelar diskusi penting di Kampus Baranangsiang, Bogor.
Diskusi ini menjadi ajang sosialisasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 16 tentang Hak atas Pangan yang baru dikeluarkan Komnas HAM. Satu pesan kunci yang mengemuka: pangan bukan sekadar komoditas dagang atau bantuan sosial, melainkan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu untuk hidup bermartabat.
Komisioner Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menjelaskan bahwa SNP No 16 disusun untuk mengisi kekosongan panduan hukum yang komprehensif tentang hak atas pangan. Dokumen ini menjadi “tafsir resmi” yang mengikut secara moral bagi negara dalam menjalankan kebijakan pangan, sekaligus panduan bagi aktor nonnegara, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam menghormati dan memenuhi hak pangan warga.
Poin paling mendasar dari SNP adalah pergeseran cara pandang. Analis kebijakan Komnas HAM, Delsy Nike, menekankan bahwa keberhasilan pangan selama ini sering diukur sebatas ketiadaan kelaparan.
“SNP No 16 menuntut standar yang lebih tinggi, yaitu pemenuhan Hak atas Pangan yang Layak,” ujarnya. Menurut dokumen SNP, pangan layak mencakup empat pilar: ketersediaan berbasis produksi berkelanjutan (bukan impor), keterjangkauan ekonomi dan fisik (harga dan barang mudah dijangkau hingga pelosok), kelayakan gizi serta penerimaan budaya, dan keberlanjutan lingkungan (tidak merusak).
Dalam sesi diskusi, Ketua Divisi Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan PSP3 IPB University, Mohamad Shohibuddin, menggunakan SNP No 16 sebagai pisau analisis untuk mengulas kebijakan Food Estate dan MBG. Ia mengingatkan bahwa proyek pangan skala besar berpotensi mengabaikan hak masyarakat adat dan keberlanjutan ekologi.
“Mengubah hutan dan rawa sagu menjadi sawah padi bukan hanya persoalan teknis, tetapi bentuk kekerasan pangan yang mencabut akar budaya masyarakat Marind Anim,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pendekatan militeristik dalam kebijakan pangan nasional melalui pelibatan batalyon penyangga. Alih-alih memberdayakan, hal ini justru berisiko menciptakan iklim intimidasi dan menutup ruang dialog sipil yang partisipatif dalam tata kelola pangan nasional.
Menurut Shohibuddin, model produksi pertanian pangan monokultur skala besar ini justru terjebak dalam pusaran corporate capture. Segelintir elite dan industri raksasa menjadi pihak yang paling diuntungkan dibandingkan produsen pangan kecil.
“Tanpa transparansi dan tata kelola yang baik, proyek raksasa yang militeristik ini sangat rentan menjadi ajang perburuan rente, yang pada akhirnya mengorbankan hak asasi petani kecil serta kelestarian lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek,” ia menandaskan.
Shohibuddin juga menyoroti program MBG yang menyedot anggaran besar, namun masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari celah akuntabilitas, risiko keamanan pangan, ketimpangan kualitas antarwilayah, hingga potensi dominasi korporasi yang dapat meminggirkan produsen lokal.
Sebagai penutup, diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis. Komnas HAM dan PSP3 IPB mendorong agar SNP No 16 tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi menjadi acuan utama dalam merevisi UU Pangan dan mengaudit proyek-proyek pangan nasional.
Shohibuddin menyerukan agar pemerintah melakukan desentralisasi sistem pangan. “Kembalikan kedaulatan pangan ke sistem pangan daerah, lumbung-lumbung pangan desa, dan juga pekarangan keluarga. Bukan pada proyek raksasa yang rentan korupsi,” pungkasnya. (*/Rz)