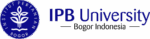Fenomena Fotografer Jalanan, Sosiolog IPB University Sebut Tanda Kontrol Sosial Baru

Fenomena fotografer jalanan menuai pro kontra akan batas antara kebebasan berekspresi dan hak privasi individu di ruang publik.
Pakar Sosiologi IPB University, Dr Ivanovich Agusta menilai fenomena ini menantang masyarakat untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi di ruang publik dan penghormatan terhadap ranah privat individu, sesuai kaidah hukum dan sosial.
“Secara normatif, berada di ruang publik sering dianggap membuat seseorang fair game untuk difoto. Namun dari sudut pandang sosiologi dan etika, batas antara ruang publik dan privat tidaklah hitam-putih,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat kini mulai membangun norma sosial baru: fotografi di ruang publik boleh dilakukan, tetapi harus beretika. “Kesadaran publik meningkat. Banyak warga menolak difoto tanpa izin. Ini tanda positif munculnya kontrol sosial baru,” tuturnya.
Bukan Zona Bebas Nilai
Ia mencontohkan kelompok rentan seperti tunawisma yang menjadikan jalan raya sebagai ruang privat sehari-hari. Artinya, ruang publik bukanlah zona bebas nilai. Dibutuhkan sensitivitas sosial dalam memperlakukan orang lain di ruang tersebut.
“Kehadiran di ruang publik tidak otomatis menghilangkan hak privasi seseorang. Walau lokasi pemotretan bersifat umum, tetap ada norma bahwa individu berhak tidak dijadikan objek visual tanpa persetujuan,” tegasnya.
Selain itu, juga menyoroti munculnya praktik komersialisasi foto di platform digital berbasis artificial intelligence (AI). Dalam beberapa kasus, orang yang difoto justru harus menebus hasil jepretan dirinya sendiri.
“Ini bentuk baru komodifikasi kehidupan sosial ketika aktivitas sehari-hari berubah menjadi barang dagangan. Citra diri seseorang diperlakukan sebagai produk yang dijual,” ujarnya.
Fenomena ini, sebutnya, sejalan dengan konsep kapitalisme digital yang dijelaskan oleh Shoshana Zuboff, yakni sistem ekonomi di mana data pribadi dijadikan komoditas bernilai tinggi untuk keuntungan perusahaan.
Mengutip pemikiran Susan Sontag, ia menambahkan bahwa setiap tindakan memotret adalah bentuk kekuasaan karena fotografer menentukan bagaimana seseorang direpresentasikan.
“Dalam konteks modern, ketika fotografer memotret pejalan kaki tanpa sepengetahuan mereka, terjadi asimetri kekuasaan fotografer melihat dan mengabadikan, sedangkan subjek terekspos tanpa kendali,” paparnya.
Menanggapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan para fotografer agar mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan etika berfotografi.
“Masalah ini tidak hanya perlu penindakan, tetapi juga edukasi. Regulasi harus diiringi literasi digital agar masyarakat tahu haknya dan fotografer memahami tanggung jawabnya,” pungkasnya.
Keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap privasi menjadi kunci agar fotografi dapat tumbuh sebagai karya seni tanpa mengabaikan martabat manusia. (AS)