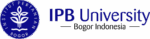Riset Mahasiswa IPB University: Gen Z Jadikan Judol Sebagai Jalan Pintas dan Hiburan Daring

Di tengah gencarnya kampanye literasi digital dan kemajuan teknologi, ada satu ironi yang pelan tapi pasti menggerogoti generasi muda, yaitu judi online (judol).
Penelitian mahasiswa IPB University mencoba menyelisik faktor di balik fenomena ini. Tim yang tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tersebut, menemukan fakta mencolok: pendidikan tinggi dan literasi digital ternyata belum cukup melindungi generasi muda dari jebakan ekonomi instan.
“Fenomena ini bukan lagi sekadar persoalan moral, tetapi cermin dari paradoks digital yang menimpa gen Z, kelompok yang lahir dan tumbuh di era konektivitas tanpa batas,” kata Zyahwa Aprilia, perwakilan tim.
Wawancara mendalam dilakukan tim kepada sejumlah responden laki-laki berusia 22–27 tahun. Mayoritas responden merupakan lulusan sarjana dengan penghasilan antara Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan.
Secara sosial, mereka hidup di tengah tekanan ekonomi kota besar, kebutuhan konsumtif meningkat, harga kebutuhan naik, sementara pendapatan belum cukup stabil.
“Sebagian responden menyatakan bahwa judol menjadi ‘jalan pintas’ untuk memenuhi gaya hidup digital. Bukan semata karena keinginan berjudi, tetapi karena keinginan untuk bertahan di lingkungan yang serba cepat dan kompetitif,” ungkapnya.
Fenomena ini, sebutnya, memperlihatkan kontradiksi. Satu sisi, mereka paham risiko digital dan telah menempuh pendidikan tinggi. Namun di sisi lain, tekanan ekonomi dan lingkungan sosial membuat mereka rentan terhadap jebakan platform daring yang menjanjikan keuntungan instan.
Penelitian ini juga menemukan pengaruh kuat budaya digital dalam normalisasi perilaku berjudi di kalangan gen Z. Iklan judol muncul di media sosial, game, bahkan grup pertemanan.
“Bagi mereka, judi digital bukan lagi aktivitas ‘gelap’, tetapi sekadar bagian dari hiburan daring. Main game sambil dapat uang, katanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi digital yang tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan literasi moral atau finansial. Akses internet justru membuka ruang bagi perilaku berisiko yang sebelumnya sulit dijangkau,” papar Zyahwa.
Fakta bahwa mayoritas lulusan sarjana menegaskan bahwa pendidikan formal belum cukup membentuk imunitas terhadap adiksi digital. Meski memiliki kemampuan berpikir kritis, dorongan sosial-ekonomi dan budaya kompetitif di media sosial mendorong mereka untuk mencari penghasilan cepat, bahkan lewat cara berisiko.
Zyahwa menyebut, kesenjangan antara kemampuan digital dan pemahaman etika digital ini menjadi titik lemah utama generasi Z. “Mereka melek teknologi, tapi belum tentu siap menghadapi kompleksitas dunia digital yang memanipulasi psikologi dan ekonomi personal,” kata dia menegaskan.
Temuan ini memperlihatkan wajah nyata “paradoks digitalisasi”. Teknologi yang diharapkan memperluas akses dan peluang justru menciptakan jebakan baru bagi mereka yang belum siap secara ekonomi dan kultural.
“Temuan ini menjadi cerminan dari banyak wilayah urban di Indonesia, cerdas, terkoneksi, tetapi rapuh di tengah derasnya arus digital. Judol hanyalah satu dari sekian banyak bentuk Specific Problematic Internet Use (SPIU), perilaku bermasalah akibat penggunaan internet yang berlebihan,” ungkap Zyahwa.
Melihat fenomena ini, Zyahwa dan tim mendorong agar kebijakan publik tidak berhenti pada pemblokiran situs. Lebih dari itu, diperlukan pendekatan sosial dan kultural yang lebih mendalam dari edukasi finansial di kampus hingga literasi etika digital di sekolah.
“Penelitian ini membuktikan bahwa angka-angka tidak berdiri sendiri. Di balik statistik, ada wajah-wajah muda yang berjuang antara realitas ekonomi dan dunia digital yang menggoda. Gen Z tidak butuh sekadar peringatan, tapi ruang aman untuk memahami dan mengelola perilaku digital mereka. Jika tidak, paradoks digitalisasi akan terus berulang, melahirkan generasi yang pintar secara teknologi, tapi kalah oleh algoritma,” pungkasnya. (*/Rz)