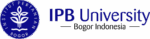Guru Besar IPB University: Agroforestri Kearifan Lokal Indonesia Efektif Pertahankan Keanekaragaman Hayati

Guru Besar Ilmu Agroforestri IPB University, Prof Nurheni Wijayanto, memaparkan secara komprehensif bagaimana agroforestri dapat menjadi jawaban untuk tantangan lingkungan dan ekonomi di Indonesia.
Prof Nurheni menjelaskan bahwa model agroforestri terbukti efektif menawarkan solusi yang adaptif untuk tiga ekosistem kunci di Indonesia, yaitu hutan tropis, lahan gambut, dan daerah pesisir.
“Hutan tropis, model agroforestri seperti kopi atau kakao dengan pohon pelindung (Shade-Grown Coffee) mampu mempertahankan keanekaragaman hayati dan mencegah erosi tanah serta menyediakan habitat satwa liar,” ucapnya.
Untuk lahan gambut, paludikultur dengan tanaman adaptif seperti sagu dan jelutung efektif mencegah kebakaran dan emisi CO₂, serta didukung praktik lokal masyarakat Dayak, seperti sistem beje (kolam ikan dengan tanaman gambut alami) dan budi daya nanas gambut serta kelakai (salah satu tanaman jenis pakis atau paku-pakuan).
Sementara di daerah pesisir, agroforestri mangrove (silvofishery) mengintegrasikan mangrove dengan tambak udang/ikan, memberikan perlindungan pantai dari abrasi dan tsunami, serta menyediakan habitat bagi biota laut.
“Dalam restorasi ekosistem kritis, silvofishery bahkan menunjukkan kapasitas penyerapan karbon yang luar biasa, yakni 3–5 kali lebih banyak dibanding hutan tropis daratan, menjadikannya strategi vital untuk ekosistem pesisir,” ujarnya.
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Lebih lanjut, Prof Nurheni mengungkap, salah satu kontribusi terpenting agroforestri adalah penyerapan dan penyimpanan karbon. Pohon pelindung, seperti Samanea saman dan Gliricidia, bersama tanaman kayu-kayuan, secara efektif menyimpan karbon di biomassa dan tanah. Di lahan gambut, praktik paludikultur secara signifikan mencegah dekomposisi gambut yang menjadi sumber utama pelepasan CO₂.
Selain itu, agroforestri berkontribusi pada pengurangan deforestasi. Dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dari lahan yang sudah dikelola, tekanan terhadap hutan alam untuk eksploitasi dapat berkurang.
“Agroforestri juga mampu mengurangi emisi dari pertanian konvensional. Penggantian pupuk kimia dengan pupuk hijau, terutama dari tanaman legum, dapat menurunkan emisi N₂O. Integrasi ternak dengan pakan berbasis daun legum pun membantu mengurangi emisi metana,” tegasnya.
Tak hanya mitigasi, agroforestri juga esensial untuk adaptasi. Sistem ini meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi melalui diversifikasi tanaman, mengurangi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem.
Dari sisi lingkungan, akar pohon menstabilkan tanah dan mencegah erosi serta banjir, sementara agroforestri juga memodulasi iklim mikro dengan naungan pohon yang menurunkan suhu lokal dan mengurangi evaporasi.
Kearifan Lokal
Prof Nurheni mencontohkan beberapa studi kasus keberhasilan agroforestri di Indonesia. Sistem Repong Damar (Krui, Lampung) yang mengombinasikan damar mata kucing, kopi, lada, dan buah-buahan berhasil mempertahankan 80% keanekaragaman hayati setara hutan alam, menyimpan karbon tinggi, dan memberikan ekonomi berkelanjutan.
“Agroforestri karet-rimba di Jambi dan Sumatera Selatan, yang menggabungkan penanaman karet alam dengan pohon hutan asli, mampu memulihkan tanah terdegradasi dan meningkatkan hasil karet hingga 30 persen dibandingkan sistem monokultur,” jelasnya.
Program lain yang sukses termasuk Paludikultur Gambut di Kalimantan Tengah, yang menggunakan penanaman jelutung, sagu, dan purun untuk mengembalikan hidrologi gambut dan mengurangi kebakaran lahan gambut hingga 70 persen.
Silvofishery Mangrove di Demak, Jawa Tengah, yang mengintegrasikan tambak udang/bandeng dengan mangrove berhasil mengurangi abrasi pantai dan meningkatkan produktivitas udang hingga 40 persen.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Kunci Keberhasilan
Prof Nurheni menjelaskan bahwa keberhasilan adopsi agroforestri berkelanjutan di Indonesia sangat bergantung pada sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan, meliputi penyederhanaan perizinan (Permen LHK No. P.24/2020), subsidi bibit, pembebasan PBB untuk lahan agroforestri berkelanjutan, serta sertifikasi produk (SVLK). Program nasional seperti Perhutanan Sosial (target 12,7 juta ha), Gerakan Nasional Pemulihan DAS, dan Desa Mandiri Peduli Gambut juga menjadi tulang punggung.
“Peran partisipasi masyarakat merupakan aktor kunci dalam keberhasilan agroforestri. Kearifan lokal dan praktik tradisional seperti Sistem Repong Damar dan Kebun Talun menjadi bukti adopsi pola tanam campuran secara turun-temurun,” ungkapnya.
Kelembagaan lokal seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Adat mempermudah akses bantuan dan pengelolaan. Inisiatif swadaya, seperti Bank Benih Komunitas dan pemasaran kolektif produk, juga berkembang.
“Kunci keberhasilan model-model ini terletak pada pelibatan masyarakat, diversifikasi hasil, pendekatan adaptif sesuai kondisi hidrologi dan salinitas, serta dukungan kebijakan seperti sertifikasi produk ramah lingkungan,” jelasnya.
Prof Nurheni menyimpulkan bahwa agroforestri bukan hanya teori, melainkan solusi nyata yang telah bekerja di lapangan dengan dampak positif yang signifikan, menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif, diversifikasi hasil, dukungan kebijakan, dan restorasi berbasis ekosistem. (AS)