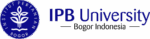Bedah Konflik Agraria, Soroti Reklamasi Kepulauan Seribu dan “Transmigrasi Lokal” Masyarakat Rempang

Dr Rina Mardiana, Dewan Penasihat Pusat Studi Agraria IPB University mengupas tuntas isu seputar alokasi lahan, konflik agraria, dan tantangan keadilan di pulau-pulau kecil Indonesia. Secara khusus, ia memaparkan analisisnya terkait yang terjadi di Kepulauan Seribu dan Kepulauan Riau.
Kepulauan Seribu: Tekanan Penduduk dan Reklamasi
Dr Rina, mengungkapkan bahwa Kepulauan Seribu, dengan ratusan pulau kecil, menghadapi masalah sedimentasi dan pengerukan pasir yang mengurangi jumlah pulau. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hanya 11 pulau yang berpenghuni dari total 110 pulau.
“Pulau Seribu Utara menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di pulau kecil se-Indonesia,” ungkapnya dalam acara Kuliah Hybrid “Ekologi Politik Pulau Kecil di Indonesia: Kasus Kepulauan Seribu dan Kepulauan Riau”, beberapa waktu lalu.
Keterbatasan lahan ini, sebut Dr Rina, mendorong masyarakat melakukan reklamasi “dari bawah” secara bertahap, yang sering kali berkonflik dengan kawasan Taman Nasional Laut. Di sisi lain, reklamasi “dari atas” oleh investor dengan modal besar juga terjadi.
“Perbedaan perlakuan reklamasi antara masyarakat dan investor menimbulkan pertanyaan keadilan,” jelasnya.
Masih di Kepulauan Seribu, Pulau Kelapa Dua mengalami perluasan signifikan akibat reklamasi mandiri oleh komunitas Bugis. Sementara itu, Pulau Pari di selatan menghadapi konflik klaim lahan oleh pihak swasta untuk pariwisata.
Pulau Rempang: Konflik Relokasi dan PSN
Lain halnya di Pulau Rempang di Kepulauan Riau. Sebagai bagian dari kawasan Barelang, kawasan ini menjadi fokus konflik terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
“Proyek yang sempat terhenti karena indikasi korupsi di masa lalu ini kembali bergulir dan menuai penolakan masyarakat adat Melayu yang telah lama mendiami 16 kampung tua,” jelas Dr Rina.
Menurutnya, pengerahan aparat dalam proses pengukuran lahan memicu dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat menolak relokasi, yang kemudian diubah narasi menjadi “transmigrasi lokal”.
Dr Rina yang juga sebagai dosen Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University menilai narasi “transmigrasi lokal” sebagai eufemisme untuk relokasi paksa.
Ia berpandangan bahwa pemindahan paksa berpotensi menimbulkan “tragedy of the commons” dan mengancam kedaulatan pangan lokal. Konflik horizontal juga muncul dengan warga Tanjung Banon yang menolak wilayah tangkap mereka digunakan oleh warga relokasi.
“Masyarakat adat Rempang bersikeras mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka dan mempertanyakan mengapa pembangunan harus mengeksklusi masyarakat tradisional,” tegasnya.
Di samping itu, ketidakjelasan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) dan desain proyek menambah kekhawatiran.
Sebagai perbandingan, ia mencontoh keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal di Pulau Penyengat. Masyarakat Rempang tidak menolak pembangunan atau investasi, tetapi menuntut mekanisme yang adil dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
“Sebagai negara kepulauan, pembangunan dan pariwisata di pulau-pulau kecil harus melibatkan masyarakat secara aktif melalui konsultasi yang bermakna, menghormati hak-hak mereka, dan memperhatikan keberlanjutan sosial-ekologis,” tandasnya. (AS)